
Ini Perbedaan Rumusan Dasar Negara dari 3 Tokoh di Sidang BPUPKI
Perumusan dasar negara diusulkan pada sidang BPUPKI oleh tiga pendiri negara. Apa perbedaan rumusan dasar negara dari ketiganya? [972] url asal
#dasar-negara #bpupki #pancasila #soekarno #muhammad-yamin #dr-soepomo #perumusan-pancasila #perbedaan-gagasan-dasar-negara #ir-soekarno #jepang #lahir #persatuan-indonesia #mohammad-hatta #dokuritsu-junbi-cosakai

Gagasan mengenai dasar negara diusulkan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh Ir Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr Soepomo. Apa perbedaan usulan dari ketiga tokoh tersebut?
Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944, Letnan Jendral Kumakici Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada 29 April 1945. Tujuannya adalah untuk melakukan segala persiapan sebelum membentuk negara merdeka yang berdaulat, termasuk merumuskan dasar negara.
Di gedung Chuo Sangi In, sidang BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini dihadiri oleh hampir 68 tokoh pergerakan nasional, termasuk Muhammad Yamin, Dr Soepomo, dan Ir Soekarno, yang merupakan tokoh perumusan Pancasila.
Pada sidang tersebut, ketiga tokoh pendiri negara mengusulkan gagasan mengenai dasar negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Rumusan Dasar Negara Menurut Muhammad Yamin
Mengutip buku Kisah Pancasila yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada 2017, perumusan "Pancasila" sebagai dasar negara dimulai pada hari Selasa, 29 Mei 1945, ketika seorang ahli hukum bernama Muhammad Yamin memulai pidatonya berjudul "Republik Indonesia".
Dalam pidatonya, dia membuka pemaparan dengan menceritakan sejarah kerajaan kuno Nusantara. Ia berpendapat bahwa perumusan dasar negara perlu dilihat berdasarkan aspek sejarah masyarakat Indonesia.
Menurutnya, Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Sriwijaya sebagai "Negara Indonesia Pertama" dan Kerajaan Majapahit sebagai "Negara Indonesia Kedua".
Setelah memaparkan sejarah dan berbagai teori politik, ia kemudian menutup pidatonya dengan mengusulkan lima prinsip yang harus dimiliki Indonesia dalam dasar negara, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Rumusan Dasar Negara Menurut Soepomo
Pada 31 Mei 1945, Dr Soepomo mengusulkan pemikirannya mengenai dasar negara dalam pidato berjudul "Negara Totaliter". Ia membuka pidatonya dengan memberikan pemaparan mengenai berbagai teori yang dikemukakan oleh para pemikir Eropa.
Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia hendaknya disusun atas dasar sifat khas masyarakat Indonesia dan bukan "menjiplak" sifat masyarakat luar negeri. Ia juga dengan tegas mengkritik kebudayaan Barat yang dinilai terlalu bersifat "individualis" dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan.
Usai berpidato, Soepomo kemudian mengusulkan beberapa prinsip yang perlu dimasukkan dalam dasar negara Indonesia, yaitu:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
Rumusan Dasar Negara Menurut Soekarno
Pada 1 Juni 1945, giliran Ir Soekarno menyampaikan gagasannya melalui pidato yang berjudul "Negara Pancasila". Ia memulai pidatonya dengan mengajukan pertanyaan "Apa itu kemerdekaan?" kepada para hadirin dalam sidang BPUPKI.
Menurut Soekarno, kemerdekaan bukan tujuan akhir dari suatu negara, melainkan adalah "jembatan emas," yang mengantarkan kepada cita-cita kebangsaan.
Soekarno juga menambahkan bahwa dasar negara tidak perlu dibuat berdasarkan teori "pelik" dan "terperinci", melainkan dibangun berdasarkan prinsip sederhana yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia sehari-hari.
Di depan tokoh-tokoh pergerakan nasional, Soekarno menyampaikan lima asas negara yang ia sebut sebagai "Pancasila", yaitu:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan
Perbedaan Usulan Dasar Negara dari 3 Tokoh
Merangkum Modul 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) "Saya Indonesia Saya Pancasila" yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berikut perbedaan usulan dasar negara dari tiga pendiri negara.
1. Diksi yang digunakan dalam setiap rumusan
2. Urutan sila-sila (atau poin) yang diusulkan
3. Jumlah rumusan yang diusulkan. Muhammad Yamin mengusulkan total 10 rumusan (5 tertulis dan 5 lisan), Soepomo dan Soekarno masing-masing 5 rumusan. Namun, secara umum ketiganya menyampaikan jumlah poin yang sama.
4. Cara penyampaian rumusan berbeda. Moh Yamin menyampaikan usulan secara tertulis dan lisan. Sementara Soepomo dan Soekarno menyampaikan secara lisan.
Hasil Keputusan Sidang
Setelah sidang selesai, BPUPKI kemudian membentuk 'Panitia Sembilan' yang diketuai oleh Ir Soekarno untuk merumuskan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang disampaikan oleh ketiga tokoh.
Akhirnya, pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyetujui rumusan "Pancasila," yang disampaikan oleh Soekarno, dengan mengubah penomoran dan menyempurnakannya menjadi:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Setelah disahkan sebagai dasar negara, rumusan Pancasila mendapat kritik oleh berbagai pihak karena dinilai hanya memasukkan unsur Islam dan melupakan unsur agama lainnya.
Akhirnya, Mohammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Usul ini diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sebagaimana dikutip dari Modul Pancasila yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015.
(faz/faz)
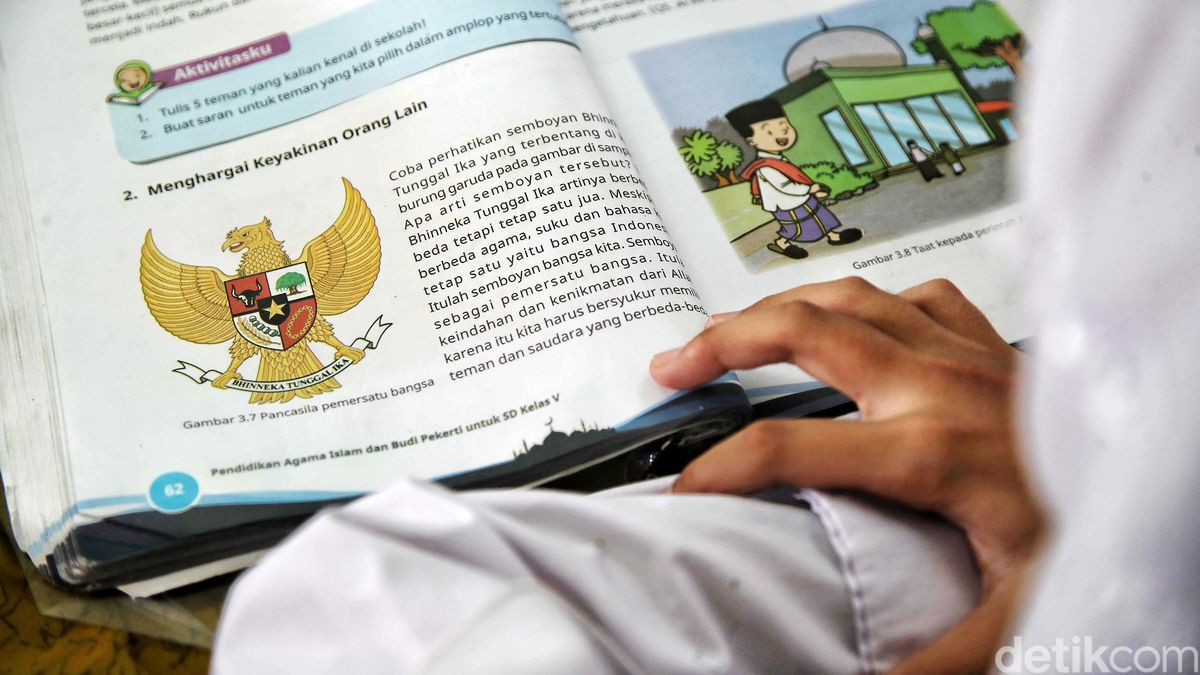
Pengertian Ideologi Beserta Sejarah, Fungsi, dan Jenisnya
Ideologi menjadi suatu pandangan yang ada di dalam masyarakat. Begini sejarahnya. [1,459] url asal
#ir-soekarno #the-wealth-of-nations #pengertian-ideologi #penyelidik-usaha-usaha-persiapan-kemerdekaan-indonesia #fasisme #martinez #lmens-didologie #fungsi-integrasi-ideologi #integrasi-ideologi #yunani #ideo
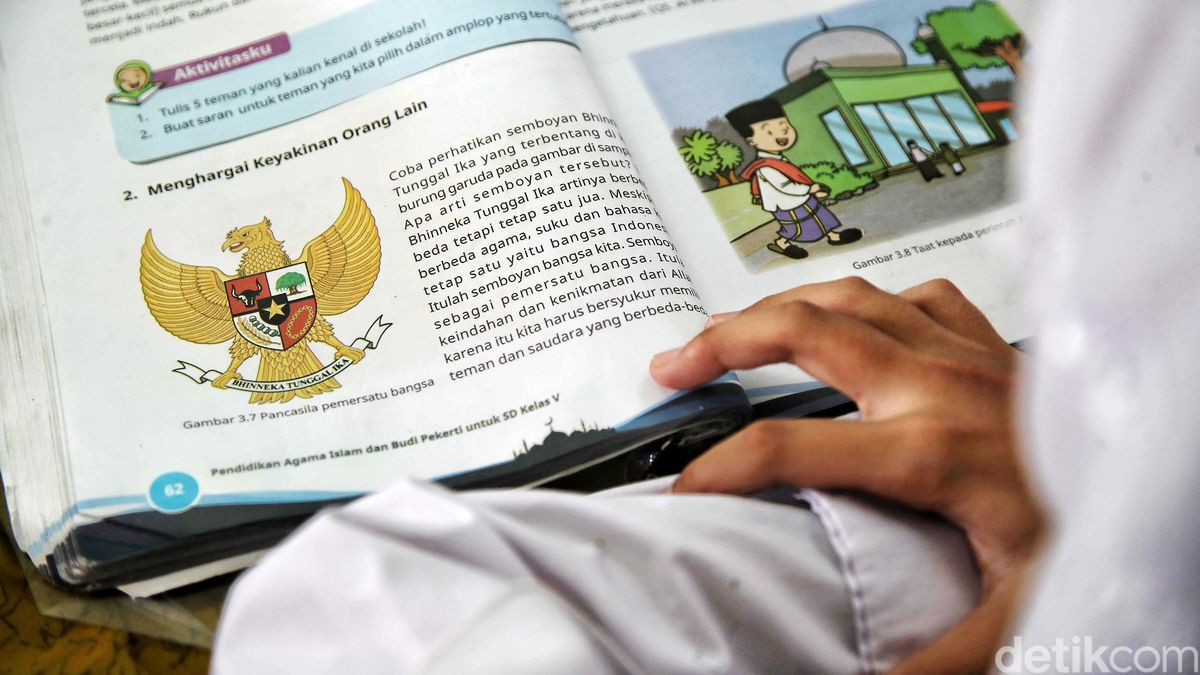
Istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh filsuf asal Prancis, Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "ilmu tentang ide". Ideologi kemudian berkembang dari gagasan tentang cita-cita masyarakat yang diperjuangkan melalui gerakan politik untuk mencapai tujuan bersama.
Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yakni "ideos" yang berarti gagasan, dan "logia" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara sederhana ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang gagasan, keyakinan, dan cita-cita.
Ada beberapa ideologi yang dikenal di seluruh dunia, mulai dari kapitalisme, sosialisme, hingga pancasila.
Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli
Karl Marx
Menurut filsuf asal Jerman ini, ideologi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama.
Thomas Hobbes
Menurut filsuf asal Inggris ini, ideologi adalah cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.
Descartes
Sebagai penemu filsafat modern, Descartes mendefinisikan ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia.
Frans Magnis Suseno
Menurut pengajar filsafat di Driyarkara School of Philosophy ini, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu.
Sejarah Kemunculan Ideologi
Menurut buku "The European Experience" dalam chapter "Ideologies in Modern History" (2023) karya Martinez dan Haan, yang dikutip Kamis (10/10/2024), istilah "ideologi" pertama kali dicetuskan oleh filsuf dan revolusioner Prancis bernama Antoine Destutt de Tracy sekitar tahun 1797.
Melalui buku berjudul "Élémens d'idéologie", Tracy mendefinisikan ideologi sebagai "ilmu tentang ide" atau "science of ideas". Konsep ideologi ini menjadi landasan berpikir para revolusioner Prancis untuk melakukan revolusi pada 1789.
Setelah revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte yang semula mendukung ide-ide dari Destutt de Tracy, kemudian mulai merendahkan para pendukungnya dengan menyebut mereka sebagai "ahli metafisika" atau orang yang dianggap gagal memahami realitas kekuasaan.
Sejarawan Jerman, Reinhard Koselleck, menyebut periode 1750 hingga 1850 sebagai Sattelzeit, yakni masa transisi ketika banyak orang Eropa mulai percaya bahwa masyarakat di masa depan bisa diatur dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan direncanakan secara sistematis
Pemikiran Koselleck tersebut memicu munculnya gerakan ideologi. Hal ini juga yang melahirkan sufiks atau akhiran kata "isme" pada setiap ideologi yang telah menjadi sebuah gerakan, seperti liberalisme, sosialisme, nasionalisme dan sebagainya.
Fungsi Ideologi
Dikutip dari buku "Sejarah Ideologi Dunia" (2015) karya Santoso, terdapat beberapa fungsi dari ideologi, diantaranya:
- Fungsi Etis
Ideologi memiliki fungsi yakni sebagai panduan dan sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
- Fungsi Integrasi
Ideologi berfungsi sebagai nilai yang menjadi pengikat suatu bangsa atau masyarakat.
- Fungsi Kritis
Dalam hal ini, ideologi memiliki fungsi sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu.
- Fungsi Praxis
Ideologi berfungsi sebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah konkrit.
- Fungsi Justifikasi
Ideologi berfungsi sebagai nilai pembenar atas suatu tindakan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu kelompok tertentu.
Jenis-jenis Ideologi
Kapitalisme
Ideologi ini mengacu pada sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik pribadi atau privat. Sistem ini memungkinkan seseorang untuk melakukan proses produksi, distribusi dan pertukaran kekayaan yang dimiliki secara pribadi.
Kapitalisme pertama kali berkembang di Inggris pada abad ke-18 M. Munculnya kapitalisme dipicu oleh gerakan individualisme dan liberalisme dalam bidang ekonomi, setelah adanya campur tangan para penguasa terhadap perusahaan swasta, seperti kebijakan monopoli dan pemberlakuan pajak yang memberatkan para pengusaha.
Atas dasar tersebut, masyarakat pada masa itu menginginkan suatu sistem yang memperbolehkan seseorang untuk berdagang secara bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah.
Buku "The Wealth of Nations" (1776) karya Adam Smith menjadi tonggak utama dalam pergerakan ini karena menginspirasi rakyat untuk memperoleh kemakmuran dan mengejar kepentingan individu tanpa keterlibatan negara.
Sosialisme
Ideologi ini berdasar pada kaum pekerja atau buruh sendiri yang menguasai alat-alat produksi serta merencanakan ekonomi secara demokratik. Sistem ini menekankan bahwa status kepemilikan swasta harus dihapuskan, terutama pada komoditi penting seperti air, listrik dan bahan pokok.
Istilah sosialisme pertama kali digunakan oleh kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 dan ke-20. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan prinsip solidaritas dan kesetaraan masyarakat.
Hal ini muncul sebagai akibat dari penerapan sistem kapitalisme yang dinilai hanya menguntungkan penguasa dan pemilik modal.
Komunisme
Istilah komunis pada awalnya memiliki dua pengertian, yakni "komune" (commune) yang berarti suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasi komune-komune itu. Pengertian lainnya dari komunis adalah milik atau kepunyaan bersama.
Paham komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Komunis yang diterbitkan pada 21 Februari 1848. Komunisme muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19. Prinsip komunisme mengajarkan bahwa semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.
Menurut ajaran komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari buruh. Namun dalam proses organisasinya, buruh hanya dapat berhasil apabila bernaung di bawah partai Politik. Dengan demikian, perubahan sosial harus dilakukan melalui peran Partai Komunis. Selain itu, komunisme menginginkan suatu sistem sosial dengan masyarakat tanpa kelas.
Liberalisme
Liberalisme berasal dari bahasa Latin "Libertas" dan bahasa Inggris "Liberty" yang berarti kebebasan. Awalnya liberalisme merupakan ajaran teologi dan filsafat mengenai kebebasan kehendak.
Paham ini menghendaki kebebasan individu di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, serta kebebasan sebagai warga negara.
Liberalisme berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 di Prancis dan Inggris. Ideologi ini muncul sebagai protes terhadap kekuasaan gereja, raja, dan para bangsawan yang dianggap mengekang kebebasan individu untuk berpikir, berpendapat, dan bertindak.
Gerakan renaissance dan aufklarung membangkitkan kembali tradisi berpikir Yunani Kuno yang mengedepankan pola pikir rasional dan pragmatis, sebagaimana dikutip dari studi "Pendidikan dan Paham Liberalisme" (2008) karya Moch Tolchah.
Nasionalisme
Nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu "nasional" yang berarti kebangsaan, dan "isme" yang berarti paham. Kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, serta memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa dan memelihara kehormatan bangsa.
Nasionalisme pertama kali berkembang pada masa Revolusi Prancis yang ditandai dengan munculnya slogan "liberté, égalité, fraternité,". Slogan ini menunjukkan adanya "kesadaran nasional" masyarakat Prancis untuk bersatu melawan kekuasaan yang otoriter.
Pada dasarnya, nasionalisme menekankan perlunya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi pada kepentingan bersama sebagai suatu bangsa. Paham ini identik dengan solidaritas dalam menghadapi musibah dan ketidakberuntungan sebagai sesama warga negara melalui persatuan dan kesatuan, sebagaimana dikutip dari studi "Nasionalisme" (2004) karya Kusumawardani dan Faturochman.
Fasisme
Fasisme adalah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa adanya demokrasi. Paham ini menekankan ultra-nasionalisme dan keotoriteran seorang pemimpin. Fasisme biasanya muncul sebagai reaksi terhadap liberalisme.
Kebebasan individu dan kebebasan berpikir yang digaungkan oleh liberalisme dinilai gagal dalam mewujudkan masyarakat yang teratur. Dalam pandangan fasisme, liberalisme justru memicu kekacauan dan mengancam stabilitas nasional.
Oleh karena itu, fasisme menolak konsep demokrasi dan menekankan kepemimpinan otoriter yang tegas dan absolut.
Pancasila
Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, asas atau prinsip. Berdasarkan arti kedua kata tersebut, pancasila dapat diartikan sebagai paham mengenai lima dasar atau lima prinsip mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengutip situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Soekarno mengemukakan lima konsep dasar pancasila yang kemudian dijadikan sebagai rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Rumusan sila pertama yang semula adalah "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya" kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku bangsa serta agama.
(faz/faz)

